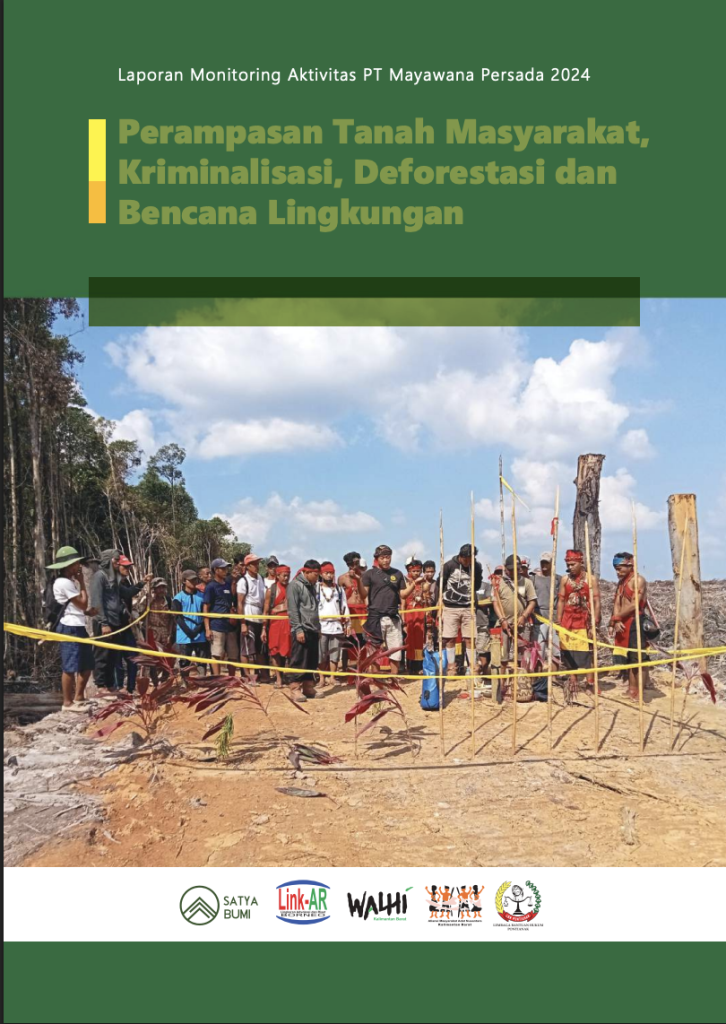Jakarta – Debat keempat Capres dan Cawapres usai digelar pada Senin (21/1/2024) malam di Jakarta. Dalam debat kali ini, para kandidat cawapres memaparkan visi misi paslon terkait pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup, sumber daya alam, energi, pangan, agraria dan masyarakat adat dan desa.
Sayangnya, dalam debat berdurasi 2 jam ini, semua kandidat gagal melihat krisis iklim sebagai permasalahan yang kompleks dan utuh sebagai satu kesatuan. Padahal seharusnya kerangka mengenai krisis iklim ini yang menjadi hal utama yang harus dihadapi karena berdampak pada kebutuhan untuk transisi energi, krisis pangan dan banyaknya bencana. Acara debat justru dipenuhi dengan gimik-gimik dan serangan personal yang minim substansi.
Sejumlah program yang ditawarkan kandidat tertentu juga sesungguhnya menyimpan potensi masalah namun luput dielaborasi lebih jauh oleh kandidat lain.
Bahan bakar nabati seperti biodiesel dengan turunan B35 dan B40, misalnya, luput dielaborasi mengenai potensi masalah perebutan CPO untuk energi vs pangan. Selama 2020-2022 rerata serapan pabrik biodiesel mencapai 41,5 persen, meningkat dibandingkan tahun 2019 yang hanya 34,5 persen. Kemudian diserap oleh industri oleokimia sekitar 10 persen, dan sisanya industri pangan. Sehingga kekhawatiran kelangkaan dan tingginya minyak goreng (CPO untuk pangan) dapat muncul kembali.
Menurut Direktur Eksekutif Satya Bumi Andi Muttaqien hingga saat ini belum ada rancangan jelas menyoal pembagian CPO untuk kebutuhan energi dan pangan.
“Selama ini harga CPO lebih stabil untuk keperluan energi ketimbang pangan. Maka jangan heran ketika harga minyak goreng menjadi melambung tinggi,” ujar Andi.
Permasalahan biodiesel harus dilihat lebih jauh dari sekadar target bauran energi. Penelitian yang dilakukan Satya Bumi bersama Sawit Watch memperlihatkan bahwa tata kelola minyak sawit di hilir masih lemah.
Jika pemerintah terus berambisi dengan bauran biodiesel tanpa menyelesaikan konglomerasi industri sawit yang bermain hingga lebih dari 60% membuat pengawasan menjadi sulit dilakukan. Tanpa memperbaiki tata kelola hilir termasuk membenahi kebijakan dua harga untuk DMO dan ekspor, bukan tidak mungkin ambisi biodiesel justru menewaskan lebih banyak lagi anggota rumah tangga di Indonesia.
Belum lagi ambisi peningkatan campuran biodiesel hingga B50 akan berpotensi secara tidak langsung menimbulkan deforestasi melalui pembukaan lahan hutan untuk perkebunan sawit yang lebih luas untuk memenuhi permintaan komoditas.
Hal ini pernah terjadi dalam kurun waktu 2014 hingga 2020 dimana terdapat peningkatan seluas 4,25 juta hektare lahan sawit dimana tahun 2016 terjadi peningkatan terbesar pasca kebijakan insentif sawit melalui BPDPKS.
Hingga tahun 2021, luas perkebunan kelapa sawit telah menempati sekitar 84,34% lahan perkebunan di Indonesia. Sementara, luas hutan menyusut dengan rata-rata 0,3% per tahun sejak tahun 2001. Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia banyak dikritisi oleh pemerhati lingkungan karena menjadi salah satu penyebab utama deforestasi di Indonesia, hilangnya keanekaragaman hayati, dan penyumbang emisi.
Hilirisasi terutama nikel juga terus disebut sebagai program unggulan salah satu kandidat. Hal ini menimbang Indonesia sebagai produsen terbesar nikel di dunia dengan cadangan hingga 21 juta metrik ton.
Andi Muttaqien juga menyebut saat ini tata kelola nikel masih semrawut. Ambisi percepatan transisi energi justru dijadikan ladang bisnis alih alih kepentingan lingkungan dan masyarakat sehingga mengakibatkan eksploitasi yang tidak terkontrol. Belum lagi masalah deforestasi, pencemaran dan perusakan lingkungan serta permasalahan ketenagakerjaan.
Deforestasi dan kerusakan lingkungan akibat tambang nikel juga semakin masif di Indonesia, khususnya di Sulawesi sebagai daerah penghasil cadangan nikel yang utama dan terbesar. Satya Bumi mencatat dari tahun 2001 sampai 2019 deforestasi di Sulawesi mencapai angka seluas 2.049.586 hektar. Deforestasi terbesar terjadi pada tahun 2015 seluas 226.260 hektar, tahun 2016 seluas 190.667 hektar dan tahun 2019 mencapai luasan 159.891 hektar.
Berdasarkan wilayah, deforestasi terbesar terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah dengan luasan mencapai 722.624.05 hektar, kedua pada Provinsi Sulawesi Tenggara yang mencapai luasan 512.465.40 hektar dan ketiga Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai luasan deforestasi 333.364.55 hektar.
“Hilirisasi tidak boleh sampai memberikan kerugian yang akhirnya lebih besar kepada manusia dan alam,” jelas Direktur Eksekutif Satya Bumi, Andi Muttaqien.
Sudah sepatutnya pemerintah, dalam hal ini paslon capres dan cawapres, menawarkan program berbasis etika lingkungan dengan pendekatan ekosentrisme, yakni perlindungan lingkungan dengan melihat seluruh kepentingan ekosistem, alih-alih pendekatan antroposentrisme yang melihat kepentingan manusia sebagai elemen sentral.