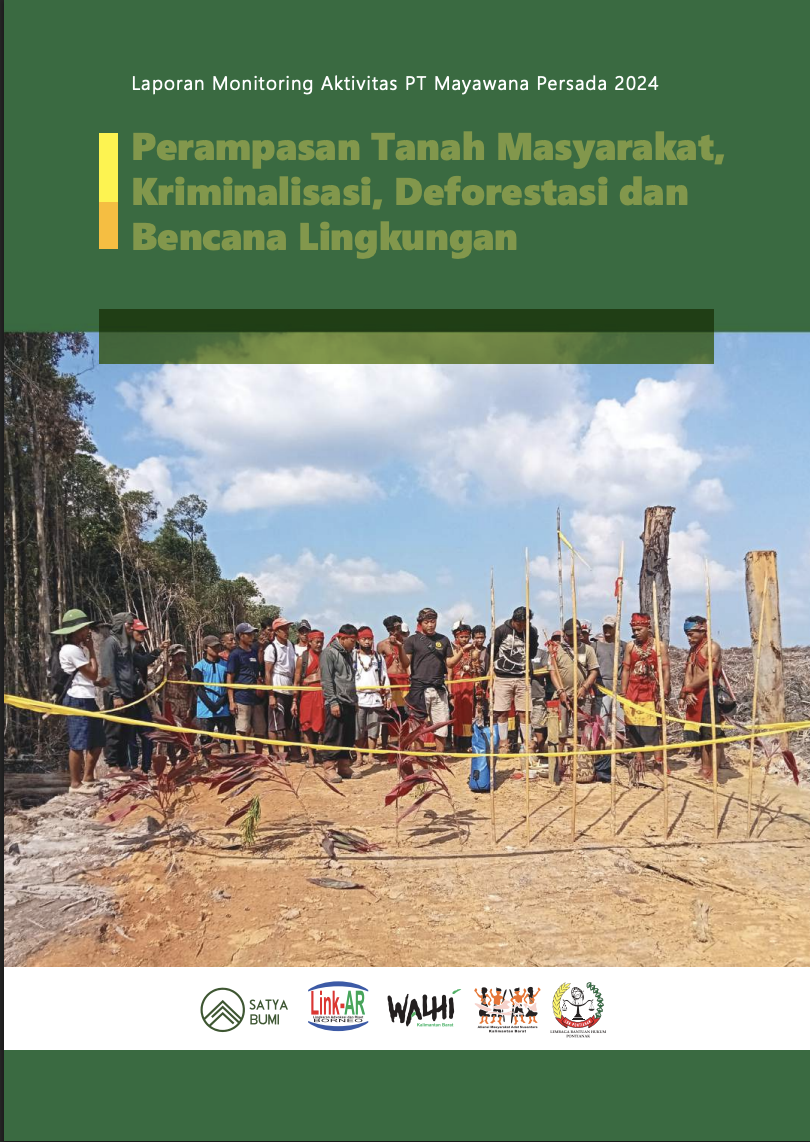Kabaena, sebuah pulau kecil di ujung Sulawesi Tenggara. Saat ini, sekitar 73 persen atau 650 km² dari total luas wilayah Kabaena yang mencapai 891 km² telah terisi puluhan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Kabaena secara konstitusional dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU No. 1/2014), yang secara tegas melarang kegiatan pertambangan di pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari 2.000 km². Namun, bagian selatan Kabaena—yang secara administratif berada di Kabupaten Buton Tengah—merupakan salah satu wilayah yang menghadapi tekanan paling besar, tetapi ironisnya justru luput dari perhatian publik maupun kebijakan negara. Padahal, wilayah inilah yang menjadi salah satu titik awal masuknya industri tambang nikel ke Kabaena sejak tahun 2007, dan disinilah kerusakan ekologis dan sosial mulai berlangsung secara sistemik dan masif.
Aktivitas pertambangan di pulau ini telah menyebabkan deforestasi luas, degradasi kawasan pesisir, pencemaran perairan laut, serta konflik agraria dengan masyarakat adat dan lokal yang belum terselesaikan selama hampir dua dekade. Hasil riset terbaru Satya Bumi, WALHI Sulawesi Tenggara, dan LSM Sagori menemukan kedekatan para pemilik perusahaan dengan elit politik dan aparat negara memperkuat impunitas terhadap berbagai pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang terjadi. Beberapa di antaranya disebut-sebut memiliki koneksi kuat dengan sedikitnya lima menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Kemudian, lebih dari sekadar persoalan lokal, eksploitasi nikel di Kabaena merupakan bagian penting dari rantai pasok global industri kendaraan listrik. Banyak perusahaan baterai dan kendaraan listrik global terindikasi mendapatkan pasokan nikel dari Pulau Kabaena. Hal ini menunjukkan bahwa produk-produk kendaraan listrik yang disebut “ramah lingkungan” justru dibangun di atas kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak-hak masyarakat di daerah-daerah seperti Kabaena.